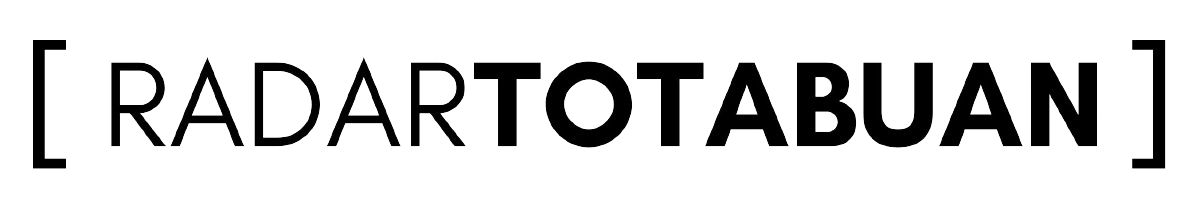Oleh: Riska Ariyanti
Mahasiswa S2 MM ESG & Sustainability Universitas Sanata Dharma
SEKTOR pertambangan merupakan arena bisnis dengan tekanan ekonomi besar, risiko lingkungan tinggi, serta interaksi kompleks dengan masyarakat lokal. Perusahaan dikejar target produksi dan profitabilitas, sementara keberadaan mereka bersinggungan langsung dengan ruang hidup masyarakat lokal, termasuk komunitas adat yang memiliki ikatan genealogis dan spiritual terhadap wilayah (Prno & Slocombe, 2012). Dinamika yang terjadi seringkali menimbulkan dilema etika dan tata kelola yang kompleks, salah satunya adalah dinamika antara perusahaan dengan masyarakat adat.
Di Murung Raya, salah satu Kabupaten di Kalimantan Tengah, ketegangan antara perusahaan tambang dan masyarakat Dayak memperlihatkan bahwa kepemilikan izin legal operasi tidak menjamin penerimaan sosial masyarakat. Perdebatan muncul antara hak eksploitasi berbasis izin pemerintah dengan klaim masyarakat atas tanah adat sebagai ruang kosmologis dan budaya. Situasi ini menegaskan relevansi Social License to Operate (SLO) sebagai bentuk legitimasi sosial nonlegal yang diberikan masyarakat kepada perusahaan ketika operasi tambang dianggap adil, transparan, menghormati martabat manusia dan adat, serta menghasilkan manfaat sosial yang setara. Kepemilikan legal permit tidak otomatis menjamin penerimaan sosial masyarakat terhadap operasi perusahaan (Owen & Kemp, 2013).
Pertanyaan utama yang hendak dijawab:
1. Bagaimana konsep SLO diinterpretasikan dan dijalankan dalam konteks tambang?
2. Bagaimana benturan nilai terjadi antara korporasi dan masyarakat adat/lokal dalam proses pengambilan keputusan sosial?
3. Apa dilema moral yang dihadapi oleh korporasi serta bagaimana etika bisnis serta pencapaian SLO yang etis membantu mengelolanya?
SLO dalam Korporasi Ekstraktif
Konsep SLO mulai dikenal pada awal 1990an sebagai respons terhadap krisis legitimasi industri tambang di Kanada dan Amerika Latin. Sejumlah operasi tambang memperoleh izin pemerintah tetapi menghadapi resistensi keras dari masyarakat, menciptakan kerugian besar secara ekonomi dan reputasi. Konsep ini muncul akibat kegagalan tata kelola ekstraktif konvensional yang terlalu mengandalkan izin pemerintah tetapi mengabaikan struktur sosial masyarakat (Prno & Slocombe, 2012). Praktik tersebut membuka kesadaran global bahwa legalitas formal tidak identik dengan legitimasi sosial, sehingga perusahaan memerlukan basis consent dari komunitas yang terdampak.
Sejak itu, SLO diadopsi industri pertambangan global melalui standar internasional, seperti International Council on Mining and Metals (ICMM), kebijakan International Finance Corporation (IFC), dan kerangka ESG. Di Indonesia, pendekatan SLO mulai masuk melalui integrasi konsultasi publik AMDAL, kebijakan FPIC, dan pergeseran CSR dari charity menjadi inclusive development.
Secara etis, SLO menegaskan bahwa operasi tambang harus selaras dengan aspirasi masyarakat dan bukan hanya sekadar meminimalkan resistensi sosial. Konsep SLO hadir sebagai tuntutan sosial bagi korporasi untuk menjalankan praktik yang adil, inklusif, dan etis. SLO menuntut dialog bermakna, pembagian manfaat yang adil, perlindungan hak adat, dan konsistensi perusahaan dalam membangun kepercayaan jangka panjang serta menjembatani perbedaan kepentingan antar-pemangku kepentingan (Komnitsas, 2020). Dengan demikian, SLO bukan hanya instrumen manajemen risiko, tetapi kerangka etika yang mendasarkan keberlanjutan pada martabat manusia dan keadilan sosial. Persetujuan sosial bukan sekadar penerimaan pasif, tetapi proses negosiasi dinamis terkait hak, identitas budaya, distribusi manfaat, dan tata kelola sumber daya (Bebbington et al., 2018).
Dalam perspektif etika, Melé (2019) menekankan bahwa hubungan perusahaan–komunitas tidak semata transaksional, tetapi harus berlandaskan martabat dan penghargaan terhadap manusia. Oleh karena itu, Oowen & Kemp (2013) memandang SLO sebagai praktik yang etis, bukan sekadar strategi mitigasi risiko Dilema Moral Perusahaan dalam Pengelolaan Hubungan Sosial dan Keberlanjutan Dalam dinamika konflik sosial di wilayah pertambangan, perusahaan sebagai entitas korporasi menghadapi dilema moral yang tidak sederhana. Di satu sisi, perusahaan memiliki kewajiban untuk menjaga keberlangsungan operasi, kepastian investasi, dan pemenuhan target produksi. Di sisi lain, perusahaan juga dihadapkan pada tuntutan etis untuk menghormati hak-hak masyarakat adat, menjaga martabat komunitas lokal, serta memastikan bahwa aktivitas operasional tidak merusak tatanan sosial dan budaya yang telah berlangsung lintas generasi.
Secara struktural, perusahaan pertambangan berada dalam ketegangan antara dua imperatif yang seringkali saling bertentangan. Di satu sisi, logika korporasi menuntut keberlanjutan operasi, kepastian investasi, dan efisiensi ekonomi sebagai dasar legitimasi bisnis. Perspektif ini berakar pada pendekatan tata kelola konvensional yang menempatkan izin legal dan kinerja finansial sebagai ukuran utama keberhasilan perusahaan (Prno & Slocombe, 2012). Namun, di sisi lain, perusahaan juga menghadapi imperatif sosial-etis yang menuntut perlindungan hak adat, penghormatan terhadap identitas budaya, serta pengakuan atas kedaulatan komunitas lokal. Dalam kerangka etika bisnis, Melé (2019) menegaskan bahwa perusahaan tidak dapat memperlakukan masyarakat semata sebagai pemangku kepentingan instrumental, melainkan sebagai subjek bermartabat. SLO menuntut pergeseran dari pendekatan teknokratis menuju pendekatan etis yang mengakui masyarakat sebagai mitra moral dalam pengambilan keputusan sosial.
Dalam konteks Murung Raya pada tahun 2013 silam dalam artikel berita Mongabay (Saturi, 2013), salah satu korporasi ekstraktif menghadapi konflik sosial serius dengan masyarakat lokal yang puncaknya pada pertengahan tahun tersebut. Ribuan masyarakat termasuk penambang rakyat, berusaha masuk ke area operasi yang aktif untuk mengambil material tambang dan mengusir perusahaan. Aksi ini berubah menjadi bentrokan dengan aparat keamanan (Brimob dan TNI), sebab aparat berusaha mencegah mereka masuk ke konsesi perusahaan.
Hal ini memperlihatkan bagaimana legitimasi sosial tidak selalu sejalan dengan kepatuhan formal. Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun perusahaan telah mengantongi izin operasional, ketegangan dengan masyarakat adat terkait ruang hidup, nilai budaya, dan dampak lingkungan dapat terus berakumulasi dan akhirnya meledak menjadi konflik terbuka.
Peran Etika dan SLO dalam Mengelola Dilema Moral Perusahaan
Dinamika konflik sosial di Murung Raya memperlihatkan bahwa dilema moral perusahaan tidak dapat diselesaikan hanya melalui kepatuhan hukum dan rasionalitas ekonomi. Prno dan Slocombe (2012) menegaskan bahwa kegagalan tata kelola ekstraktif konvensional terletak pada asumsi bahwa izin negara identik dengan legitimasi sosial. Ketika perusahaan mengabaikan dimensi relasional dan kultural masyarakat adat, akumulasi ketidakpercayaan berpotensi berkembang menjadi konflik terbuka, sebagaimana ditunjukkan oleh peristiwa 2013 di Kabupaten Murung Raya (Saturi, 2013).
Dalam kerangka ini, SLO berfungsi sebagai mekanisme etis yang menggeser orientasi perusahaan dari sekadar mitigasi risiko menuju pembangunan legitimasi moral (Owen & Kemp, 2013). Sejalan dengan pandangan Melé (2019), pendekatan etis SLO menempatkan masyarakat bukan sebagai pemangku kepentingan instrumental, melainkan sebagai subjek bermartabat yang memiliki hak atas persetujuan. Melalui dialog partisipatif, pengakuan hak adat, dan kesediaan menyesuaikan desain proyek, perusahaan dapat mengelola dilema moral secara konstruktif, sekaligus membangun keberlanjutan operasional yang berakar pada kepercayaan sosial jangka panjang (Bebbington et al., 2018).
Pembelajaran dari Murung Raya: Menuju Tata Kelola yang Etis dan Berkelanjutan
Pengalaman konflik sosial di Murung Raya memperlihatkan bahwa hubungan antara perusahaan pertambangan dan masyarakat tidak dapat dibangun semata melalui pendekatan kesejahteraan yang bersifat top-down atau kepatuhan administratif. Kasus ini menunjukkan bahwa legitimasi sosial tidak muncul dari besaran investasi sosial melainkan dari pengakuan terhadap identitas, agensi, dan hak kolektif masyarakat adat sebagai pemilik ruang hidup. Ketika perusahaan mengedepankan pendekatan represif atau partisipasi yang bersifat simbolik, resistensi sosial justru menguat dan konflik menjadi semakin sulit dikelola. Sebaliknya, keterlibatan masyarakat secara bermakna dalam proses pengambilan keputusan terbukti mampu menurunkan ketegangan dan membuka ruang kolaborasi yang lebih setara, sebagaimana ditegaskan oleh Prno dan Slocombe (2012) dalam kritik mereka terhadap tata kelola ekstraktif konvensional.
Dari perspektif perusahaan, kepastian hukum dan izin operasional tidak pernah cukup tanpa legitimasi sosial yang berkelanjutan. Konflik pada 2013 silam memperlihatkan bagaimana ketegangan antara logika korporasi dan nilai budaya masyarakat adat dapat terakumulasi ketika ruang dialog dan pengakuan moral tidak dibangun sejak awal (Saturi, 2013). Dalam kerangka ini, etika tidak lagi dapat diposisikan sebagai kewajiban normatif semata, melainkan sebagai strategi bisnis jangka panjang yang menentukan keberlanjutan operasi. Kepercayaan sosial yang tumbuh melalui proses etis terbukti mampu menurunkan risiko konflik, mengurangi biaya sosial dan keamanan, serta mencegah gangguan operasional yang berlarut-larut (Owen & Kemp, 2013).
Refleksi: Apa yang Dapat Dipelajari?
Pendekatan etis terhadap SLO juga memiliki implikasi internal bagi perusahaan. Ketika perusahaan memilih membangun legitimasi melalui dialog partisipatif, pengakuan hak adat, dan penerapan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC), tekanan moral di dalam organisasi turut berkurang. Perusahaan tidak lagi bergantung pada stabilitas semu atau pencitraan keberhasilan sosial, melainkan pada relasi kepercayaan yang lebih jujur dan berkelanjutan. Dalam perspektif etika bisnis, sebagaimana ditegaskan Melé (2019), pendekatan ini mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia dan menggeser relasi perusahaan–masyarakat dari yang bersifat instrumental menjadi relasi moral yang setara.
Pada akhirnya, kasus Murung Raya menegaskan bahwa dilema moral dalam industri ekstraktif bukanlah situasi tanpa jalan keluar. Ketika perusahaan menempatkan etika dan pencarian SLO yang etis sebagai fondasi tata kelola, keberlanjutan tidak lagi sekadar klaim ESG, melainkan realitas sosial yang dirasakan bersama. Pertanyaan kunci bagi industri pertambangan Indonesia ke depan bukan hanya bagaimana mempertahankan operasi, tetapi bagaimana memastikan bahwa operasi tersebut diterima secara bermartabat oleh komunitas yang hidup berdampingan dengannya.***