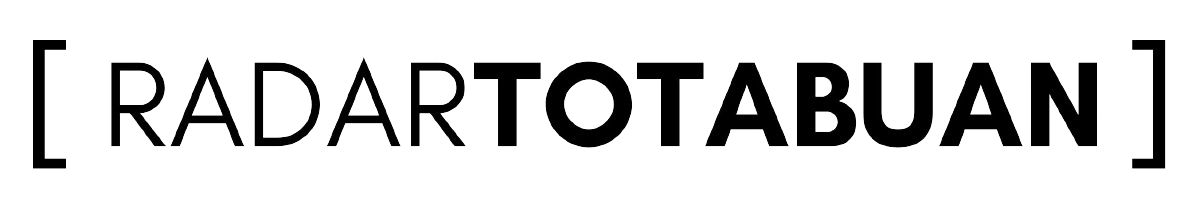JAKARTA, RADARTOTABUAN.COM – Sekitar tahun 2004-kalau ingatan saya tidak keliru-Buya Syafii Ma’arif pernah menulis di Harian _Republika_ tentang kondisi intelektual bangsa. Saya tak bisa lagi menemukan artikelnya, bahkan sudah mencoba mencarinya lewat mesin pencari. Tapi ada satu istilah yang menancap kuat dalam benak saya hingga hari ini: _*Fachidiot*_. Istilah itu kami perbincangkan pada suatu sore yang hangat di ruang kerja beliau di Kantor PP Muhammadiyah, Cik Di Tiro, Yogyakarta. Beliau sejatinya sedang mendidik saya. Saat itu, Buya adalah Ketua Umum _PP Muhammadiyah_. Saya sendiri masih mahasiswa pascasarjana di UGM dan, di saat bersamaan, menjabat sebagai Ketua _Pimpinan Daerah Muhammadiyah_ Kota Manado. Saya sering datang ke kantor itu—berguru informal, berdiskusi banyak hal. Ketika tulisan itu akhirnya terbit, saya ingat betul beliau menyebut, “Saya punya kawan dari Indonesia Timur…….” dan saya merasa sangat terhormat disebut sebagai “kawan”.
Tulisan ini adalah semacam jejak balik, pengingat akan percakapan yang terus hidup di kepala saya; tentang Fachidiot, seseorang yang cerdas dalam satu bidang, tapi kehilangan kemampuan untuk melihat kehidupan secara utuh—ahli yang tahu segalanya tentang satu titik, tapi buta terhadap garis besar.
Kini, dua dekade setelah percakapan itu, saya merasa istilah itu bukan saja relevan kembali—tapi menjadi sangat mendesak untuk dibahas.
Istilah Fachidiot mulai dikenal di Jerman sejak 1960-an, sebagai kritik terhadap kaum intelektual yang terjebak dalam lorong sempit keilmuan.
Mereka sangat piawai dalam bidangnya, tetapi tumpul dalam empati dan relasi sosial. Mampu mengurai rumus kompleks, tapi kaku menghadapi tangis orang miskin. Bisa menyusun kebijakan penuh angka, tapi tak mengenali penderitaan di balik grafik.
Inilah wajah pengetahuan yang kehilangan makna, ketika ilmu hanya jadi alat produksi, bukan alat pemahaman.
Dalam konteks Indonesia, Fachidiot bisa menjelma dalam rupa teknokrat, pejabat, atau akademisi—yang tahu sistem tapi asing dengan rasa.
Kritik Buya Syafii saat itu, ternyata adalah peringatan yang melampaui zaman.
Dari perspektif ilmu otak, Fachidiot bukan semata-mata karakter, tapi hasil dari plastisitas saraf yang timpang. Ketika seseorang terus-menerus terpapar hanya pada satu jenis informasi—misalnya _regulasi, prosedur_, atau _data teknis_—maka jalur sinaptik yang berulang di area tersebut akan menguat (ingat Doktrin Neuron dari Hebb: _’fire togheter, wire togheter_’), sementara area lain yang berkaitan dengan _empati, intuisi_, dan _nalar sosial_, menyusut.
Ini dikenal sebagai _use-dependent synaptic plasticity_. Apa yang sering digunakan akan dikuatkan. Apa yang jarang disentuh, akan menghilang.
Seorang yang brilian dalam bidangnya bisa menjadi sangat tumpul dalam membaca kompleksitas kemanusiaan. Otaknya bukan rusak, tapi terkunci dalam satu mode berpikir.
Ketika orang semacam ini memimpin, bukan korupsi yang jadi ancaman, tapi kekeringan batin dalam pengambilan keputusan. Dan itu lebih berbahaya.
Banyak dari kita mengenal orang-orang yang hebat di bidangnya—penuh prestasi, rapi secara akademik, dan berbicara seperti ensiklopedia hidup. Namun saat mereka diamanahkan memimpin, muncul kegamangan yang menyesakkan. Bukan karena tak pintar, tapi karena kecemerlangan itu terpenjara dalam ruang spesialisasi.
Mereka tak pernah benar-benar belajar mengelola kompleksitas manusia, mendengar keresahan, atau menyatukan perbedaan. Otak mereka efisien di lorong logika, tapi gagap di belokan rasa.
Lahirlah keputusan-keputusan yang secara administratif presisi, tapi menyisakan luka sosial, tiada empati. Terlihat rapi di atas kertas, tapi terasa dingin di lapangan. Di situlah letak paradoks kita hari ini: _ketika kepintaran berjalan tanpa kearifan, maka kepemimpinan kehilangan nyawa_.
Mereka tampak jenius dalam kalkulasi, tapi kaku dalam komunikasi. Mampu menghafal teori, tapi gagap saat harus mendengarkan keluhan rakyat. Ketika tantangan berubah dari sekadar sistem menjadi persoalan batin manusia—tentang harapan, ketakutan, dan perjuangan bertahan—mereka kehilangan arah.
Bahasa yang digunakan tak lagi untuk menyapa atau merangkul, tapi untuk memberi instruksi dan membungkam.